Karena Sastra Membutuhkan Rasa
“Sastra bisa menampung semua gejolak dalam diri, mengurangi derita serta membuatmu lebih peka serta berdaya.”
"Apa yang kau sukai dari sastra Ken?", tanya seorang sahabat. Pertanyaan ini ternyata masih menggantung dalam deretan terdepan dalam pikiran saya hari ini. Well, maybe karena saya dilahirkan dari keluarga yang hampir seluruhnya sangat mencintai sastra. Entah, ini seperti turun-menurun, mendarah daging, mungkin esok ketika saya memiliki anak pun kecintaan pada sastra tak akan pernah pudar. Kecintaan keluarga pada sastra seperti warna pelangi yang pendarnya sudah terlanjur terbiaskan ke seluruh warna di dunia. Ia bermetamorfosa menjadi warna-warna yang indah namun tetap ingat pada siapa akar warna mereka berada.
Sejak kecil Bapak suka sekali membelikan saya buku, bukan buku anak-anak kebanyakan namun buku-buku sastra yang saya tak pernah memahami bahasa dan alur ceritanya. Bukan seperti roman picisan jaman sekarang, lebih kepada sense of feeling ketika membaca buku-buku yang Bapak belikan. Saya ingat sekali ketika tugas Bahasa Indonesia membuat puisi, Bapak dengan semangat membelikan saya banyak sekali buku karangan Chairil Anwar (Penyair angkatan 1945), WS. Rendra yang baru-baru ini saya mengetahui bahwa beliau sahabat karib kakek saya, hingga Taufik Ismail yang saya amat favoritkan puisi-puisi religi nasionalis beliau. Buku kumpulan puisi yang saya tidak paham maknanya. Maklum, masih kecil dan belum benar-benar menjadi penikmat sastra.
Ketika pulang ke Semarang dan Bapak diundang menghadiri acara sastra dalam Bulan Bahasa, saya yang masih kecil sering ikut. Pada waktu itu hanya ikut saja, menikmati musikalisasi puisi, penyair membacakan puisinya, seperti anak kecil yang kebingungan harus berbuat apa. Diam, duduk termenung sambil sesekali menarik celana panjang Bapak untuk minta pulang. Maklum, di jaman itu acara sastra selalu dilaksanakan malam hari di bawah lampu yang temaram, tidak begitu jelas. Dari motivasi dan semangat yang luar biasa dari Bapak saya perlahan-lahan mulai mencintai sastra. Walau teman-teman agak risih ketika saya lebih suka membaca ketimbang bermain berlarian. Masa-masa sekolah di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah dihabiskan untuk menulis cerita, membuat puisi, membaca buku dan belajar. Sesekali bercanda riang dengan teman-teman, main petak umpet atau dokter-dokteran. Saya menemukan dunia baru dalam bingkai kesusastraan.
Setiap selesai membaca buku, saya selalu ingin dan ingin berdiskusi. Dengan orang yang sudah membaca buku itu pula. Membedahnya, mencari benang merah dari setiap cerita dan kekhasan penulisnya, hikmah yang didapat, diksi yang dipakai, pola bahasa dan hubungan antar kata. Semua seperti terangkum dalam satu kesatuan bernama imaji. Walau teman diskusi saya hanya keluarga, karena tidak ada teman saya yang memiliki hobi 'aneh' seperti saya ini. Siapa teman diskusi sastra, seni dan budaya selain keluarga? Hingga saat ini pun saya belum pernah menemukannya.
Suatu ketika saya membawa buku karya Habiburrahman El Shirazy ke kampus, beberapa buku karya beliau sudah rusak karena sering dipinjam dan diputar kesana kemari oleh teman-teman Bapak. Saya sengaja alias ngetes, kira-kira siapa yang mau pinjam buku saya. Ternyata tidak ada. Kemudian saya membawa tetralogi Laskar Pelangi ke kampus, dari Laskar Pelangi hingga Maryamah Karpov, juga tidak ada yang meminjam. Saya bawa buku bunda Asma Nadia dan Bunda Helvy Tiana Rosa sebagai bahan saya mengisi kajian, kebanyakan mereka juga tidak mau meminjam, hanya ingin mendengar resensi dari saya. Sedih.
“Kalau sebuah bahasa dengan kesusasteraannya tidak didukung oleh tradisi membaca masyarakatnya, maka kematiannya akan segera menyusul”
Saya sangat bersyukur ketika saya bergabung dalam komunitas Goodreads, komunitas pecinta buku, penikmat sastra dan produktif berkarya. Paling tidak ada teman berdiskusi ketika saya selesai membaca buku. Saya juga bersyukur banyak sekali buku bergenre novel bernapas islam yang diangkat ke layar lebar. Walaupun saya lebih suka membaca terlebih dahulu novel yang akan difilmkan. Saya juga bersyukur banyak penulis muda yang menerbitkan banyak bukunya untuk kemaslahatan umat. Menulis itu peduli dan menulis itu menginspirasi.
Sastra itu membutuhkan rasa. Ia bergelayut di sepanjang karya. Dan dasar dari semuanya adalah cinta. Seperti Sapardi Djoko Darmono yang melukiskan hujan begitu syahdu dalam sajak Hujan di bulan Juni, seperti Buya Hamka yang seluruh romannya menguras air mata. Semua dibuat dari rasa yang teramat dalam dan cinta yang teramat dalam pula padaNya. Bukankah Allah yang memberi rasa dan cinta hingga melahirkan banyak karya?.
Bapak selalu mengatakan: "Tulislah kata pertama, dan biarlah Allah yang menggerakkan hati dan pikiranmu, Ken". Benar yang dikatakan, bahwa sastra akan menjadikan penikmatnya lebih peka dan lebih berdaya. Kebanyakan dari sastrawan, seniman dan budayawan bergenre religi,mereka selalu menyuguhkan cerita terbaik dalam setiap masterpiece nya, dan seluruhnya ditujukan untuk yang mereka cinta, RabbNya. Barangkali ini yang dinamakan rasa. Bukan sembarang rasa, ia mengalir menjadi sakinah yang menyejukkan, dan ia akan tumbuh selama karya menjadi amal dan bekal di akhirat kelak. Aamiin.
Selamat Berkarya!. Yuk dukung Gerakan 1 hari 25 halaman membaca (BacaDuaLima) :)
Keep Reading and Keep Writing :).
“Sastra itu penuh makna dan bisa mengingatkan kita dengan cara yang indah dan tak terduga.”

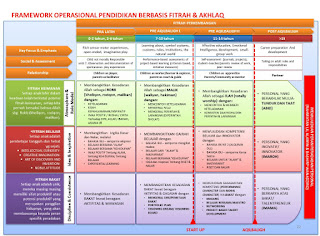
Komentar